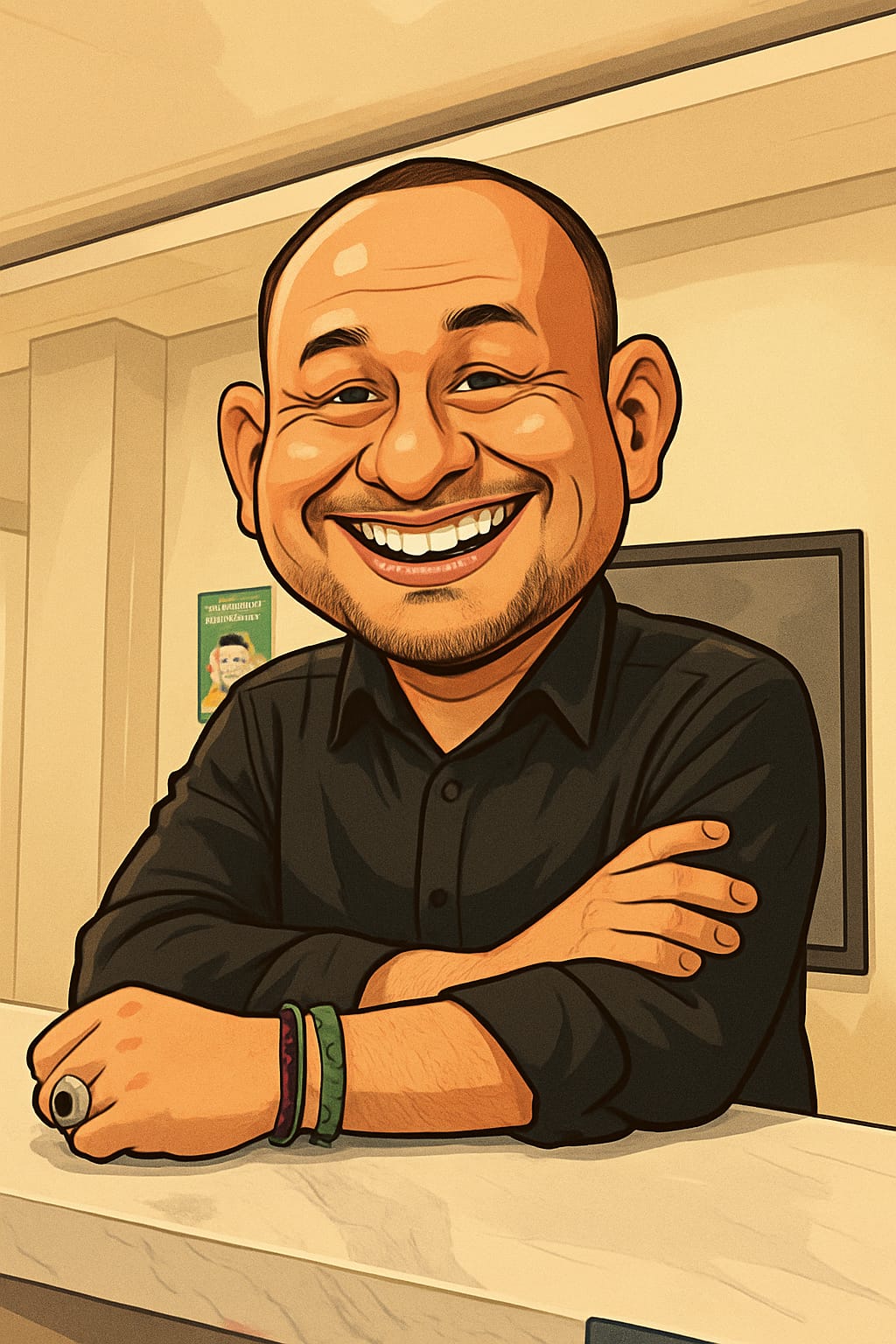Dua Kekuatan, Satu Kebuntuan: Drama Politik di Balik Mandeknya Anggaran Pidie Jaya
Foto : Dok.Google Image/ilustrasi | LIPUTAN GAMPONG NEWS
OPINI -;Pidie Jaya sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena gempa bumi, bukan pula karena minim anggaran pusat. Tetapi karena satu hal yang lebih destruktif yakni kebuntuan politik yang dibungkus rapi dalam bahasa kelembagaan. Pemerintahan jalan di tempat, pelayanan publik tersendat, dan proyek pembangunan seperti kapal tanpa nahkoda. Di balik layar, dua kekuatan besar, DPRK dan Bupati saling mengunci dengan kunci politik yang tak tampak oleh mata awam, namun jelas terasa dampaknya oleh rakyat jelata.
Konflik antara legislatif dan eksekutif di Pidie Jaya adalah potret satir dari demokrasi lokal yang kehilangan ruh. Sejak awal 2025, pembahasan APBK tak kunjung selesai. Padahal, anggaran itu ibarat darah bagi tubuh pemerintahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pembuluhnya tersumbat oleh ego politik, balas jasa, dan negosiasi. Satu pihak menuding tak dilibatkan, pihak lain merasa punya hak prerogatif. Rakyat? Hanya jadi penonton setia dalam drama politik musiman.
DPRK merasa disepelekan. Mereka menyebut usulan hasil reses tidak masuk dalam draf rasionalisasi anggaran. Mereka kecewa, dan menganggap Pemkab melangkahi peran legislatif. Tapi mari kita jujur, benarkah semua usulan itu murni suara rakyat, atau sebagian hanyalah titipan sponsor politik yang kini mulai menagih janji? Parahnya lagi, ketika desakan pansus defisit muncul, sebagian pimpinan DPRK justru menolak. Bukankah itu seperti menolak menyapu dapur sendiri karena takut terlihat kotor?
Sementara di seberang meja eksekutif, Bupati juga tidak bebas dari kepentingan politik anggaran. Terpilih lewat proses demokrasi mahal, ia memikul beban politik yang tak ringan. Loyalitas harus dijaga, kursi strategis harus diisi oleh orang kepercayaan, dan relasi kekuasaan harus dirawat demi kelangsungan kekuasaan. Dalam bahasa yang lebih halus, ini adalah bagian dari "penataan birokrasi". Dalam kenyataan, ini membuat pelayanan publik terkatung-katung dan OPD bekerja seperti tim yang kehilangan komando.
Kedua belah pihak merasa benar. DPRK merasa punya legitimasi suara rakyat, Bupati merasa punya mandat eksekutif. Tapi di antara silang pendapat dan tarik-menarik itu, yang terjepit adalah masyarakat bawah. Guru honorer yang belum terima gaji, petani yang gagal tanam karena alat bantu tak kunjung tiba, dan nelayan yang jaringnya robek tapi tak ada subsidi. Mereka menjerit bukan karena tak tahu politik tapi karena mereka jadi korban paling awal dari ketidakcakapan elit dalam berdamai.
Dan satu hal yang tak kalah getir terkait pembagian “kue pembangunan” yang dianggap tidak proporsional. Program-program prioritas dipusatkan pada kelompok atau wilayah tertentu, sementara yang lain hanya mencicipi remah-remahnya. Ketika distribusi tidak adil, maka kemarahan pun tumpah dalam bentuk lain, interpelasi yang dilontarkan, hingga unjuk kekuatan di sidang paripurna yang lebih mirip panggung opera daripada forum terhormat. Fokus bergeser dari anggaran ke ego, dari substansi ke simbol, dari pelayanan ke perlawanan.
Rakyat menjerit akibat ulah mereka. Anak-anak tak dapat gizi tambahan dari posyandu, karena dana operasional belum dicairkan. Jembatan gantung di pedalaman rusak, tapi tak kunjung diperbaiki karena belum masuk prioritas. Ibu-ibu di pasar mengeluh karena harga bahan pokok naik, tapi tak ada program intervensi ekonomi. Ini bukan salah pasar, ini salah sistem politik yang disabotase oleh para pemainnya sendiri.
Ironisnya, drama ini dikemas dengan jargon-jargon yang tampak intelek. Ada yang menyebut ini “mekanisme check and balance”, ada pula yang menyebut “penjagaan konstitusi anggaran”. Padahal yang sedang dipertahankan bukanlah kepentingan rakyat, tapi kekuasaan. Ketika anggaran dijadikan alat tawar-menawar, maka sistem pemerintahan tak ubahnya meja permainan, siapa paling berani gertak, dialah yang menang.
Lebih menyedihkan lagi, masyarakat pun tak sepenuhnya bersih dari dosa kolektif ini. Politik uang masih jadi budaya yang tak malu-malu dipertontonkan. Kampanye berbasis amplop, transaksi suara, hingga relasi “isi dompet, isi bilik suara” masih mengakar kuat. Maka jangan kaget jika yang lahir dari proses itu adalah pemimpin yang lebih lihai menghitung daripada mendengar.
Lingkaran pusingan arus ini tidak akan terputus jika hanya mengandalkan kesadaran aktor lokal. Harus ada intervensi dari atas, Pemerintah Aceh harus hadir, membuka ruang mediasi, bahkan jika perlu mengambil alih sementara pembahasan anggaran demi keberlanjutan pelayanan publik. Transparansi anggaran harus dijamin, audit APBK perlu digelar, dan ruang partisipasi publik harus dibuka lebih lebar dari sebelumnya.
Demokrasi lokal kita sedang mengalami kemunduran. Jika ini dibiarkan, maka kita hanya akan mengganti pemain tanpa mengganti permainannya. Bupati boleh berganti, anggota dewan bisa baru, tapi jika pola dan cara mainnya sama, maka lima tahun ke depan Pidie Jaya akan terus berjalan dalam lingkaran arus yang sama. Demokrasi tanpa kejujuran adalah sandiwara tanpa akhir.
Sudah saatnya dua kekuatan besar ini berhenti bermain drama. Rakyat tidak butuh aktor politik, mereka butuh pelayan publik. Pertemuan antara DPRK dan Pemkab seharusnya bukan ajang saling jegal, melainkan forum kolaborasi. Cukup sudah sandiwara ini, karena di luar sana, rakyat Pidie Jaya sedang berjuang sendiri menghadapi hidup yang tak kenal kompromi.
Jika keduanya masih terus saling mengunci, maka sejarah akan mencatat mereka bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai penghambat. Pemimpin yang abai bukan hanya gagal dalam jabatan, tapi juga gagal dalam kemanusiaan. Dan dari kegagalan itu, penderitaan rakyat akan terus membubung, menyesaki langit Pidie Jaya yang semakin muram.
Oleh : Teuku Saifullah
Warga Pidie Jaya, Aceh