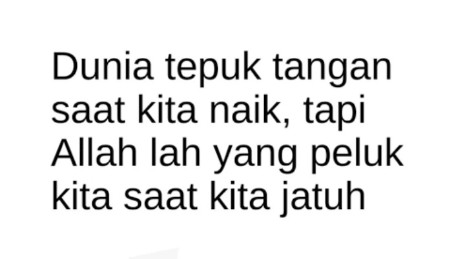Tiga Bulan Pasca Bencana, Koordinasi dengan LSM Baru Dimulai: Ada Apa dengan Tata Kelola Bencana Pidie Jaya?
OPINI - Tiga bulan setelah banjir bandang menerjang, sebagian wilayah masih menyisakan endapan lumpur di halaman rumah, lorong-lorong gampong, dan fasilitas umum. Pemandangan itu bukan sekadar sisa material bencana, tetapi simbol dari pemulihan yang belum sepenuhnya tuntas. Warga yang setiap hari melintasi sisa-sisa bencana tentu merasakan bahwa waktu berjalan lebih cepat di kalender dibandingkan perubahan di lapangan.
Di tengah situasi tersebut, ruang publik diramaikan oleh pernyataan salah seorang pejabat kabupaten yang juga menjadi korban terdampak. Suara itu memperlihatkan kegelisahan kolektif, harapan agar penanganan lebih terukur dan percepatan pemulihan benar-benar terasa. Namun yang kini menguat bukan sekadar soal kepedulian, melainkan tuntutan akuntabilitas, terutama terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) dan tata kelola bantuan.
Dalam konteks kebencanaan, BTT adalah instrumen vital yang dirancang untuk merespons kondisi darurat secara cepat. Karena itu, publik berhak mengetahui secara terbuka, berapa total anggaran BTT yang telah dialokasikan, pos penggunaannya, serta siapa saja penerima manfaatnya. Transparansi ini bukan bentuk kecurigaan, melainkan bagian dari prinsip tata kelola yang baik agar setiap rupiah benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.
Kemarin, mendekati tiga bulan pasca bencana, rapat koordinasi antara Bappeda Pidie Jaya dan sejumlah LSM akhirnya digelar. Langkah ini tentu patut diapresiasi sebagai upaya konsolidasi. Namun secara manajerial kebencanaan, publik menilai bahwa forum seperti ini seharusnya dilakukan sejak awal fase tanggap darurat atau paling lambat saat masa pemulihan sedang berjalan. Koordinasi dini penting untuk memetakan seluruh aktor yang terlibat, baik pemerintah, relawan, maupun lembaga non pemerintah.
Seharusnya, sejak minggu-minggu pertama pasca bencana, sudah tersedia data terpadu mengenai siapa saja yang masuk memberikan bantuan ke Pidie Jaya, berapa nilai logistik yang disalurkan, serta wilayah mana yang telah menerima distribusi. Tanpa pemetaan awal yang sistematis, risiko tumpang tindih bantuan atau bahkan kekosongan di wilayah tertentu menjadi sulit dihindari. Perencanaan yang solid bukan hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menjaga keadilan distribusi.
Lebih jauh, koordinasi awal juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Dengan data yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui peran masing-masing pihak, baik provinsi, kabupaten, maupun mitra eksternal. Transparansi ini akan memperkecil ruang spekulasi dan memperkuat rasa kebersamaan dalam menghadapi bencana. Ketika semua pihak tahu posisi dan kontribusinya, energi kolektif bisa diarahkan untuk solusi, bukan perdebatan.
Bencana adalah ujian solidaritas dan kapasitas tata kelola. Kritik yang muncul hari ini hendaknya dibaca sebagai dorongan perbaikan, bukan serangan personal. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperkuat sistem ke depan dengan membangun dashboard data bantuan, memperbarui laporan berkala, dan melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan distribusi.
Pada akhirnya, lumpur yang masih tersisa di Pidie Jaya bukan hanya persoalan fisik, melainkan refleksi atas pentingnya manajemen yang terencana dan transparan. Publik menuntut keterbukaan, bertanya berapa, ke mana, dan siapa yang telah menerimanya, karena di balik setiap angka anggaran, ada harapan warga untuk segera bangkit. Dan harapan itu hanya bisa dijaga dengan kerja nyata yang terkoordinasi sejak awal, bukan setelah waktu berjalan terlalu jauh. (TS)