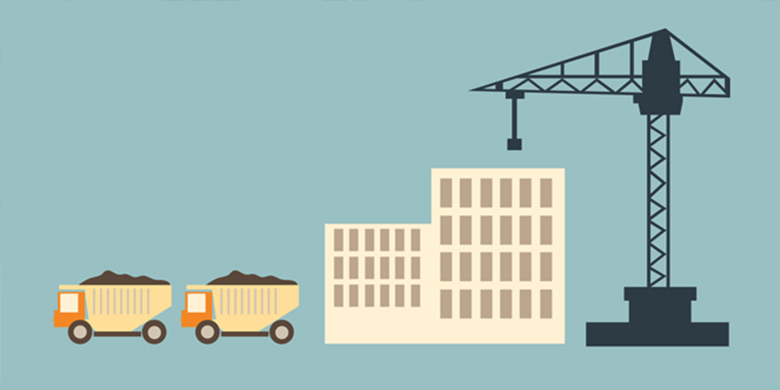Aceh di Persimpangan Tambang: Lepas dari Mulut Buaya, Diterkam Mulut Harimau
Oleh : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
OPINI - Setelah dua dekade hidup dalam damai, Aceh kini dihadapkan pada babak baru yang tak kalah getir. Jika dulu rakyat dicekam oleh ketakutan karena konflik bersenjata, kini mereka digigit oleh kekuasaan dan pemodal. Senjata memang sudah lama diam, tetapi wajah kekuasaan baru muncul dalam bentuk lain berupa izin perusahaan tambang, surat rekomendasi, dan jaringan elit yang merapat ke pengusaha besar.
Inilah paradoks Aceh hari ini, daerah yang diberi kewenangan luas lewat otonomi khusus, namun justru kehilangan kedaulatan atas tanah dan kekayaannya sendiri. Setelah lepas dari mulut buaya konflik, rakyat kini diterkam oleh mulut harimau ekonomi.
Persoalan tambang di Aceh bukan sekadar kisah tentang izin dan investasi. Ia adalah potret buram dari relasi timpang antara rakyat, penguasa, dan pemodal. Di Kabupaten Aceh Selatan, misalnya, muncul nama PT Empat Pilar Bumindo, yang disebut-sebut mengajukan permohonan rekomendasi ke beberapa keuchik di Kecamatan Samadua untuk membuka izin usaha pertambangan.
Di atas kertas, proses itu terlihat wajar, seolah mengikuti prosedur hukum. Tapi di lapangan, kabar tentang dugaan intervensi pejabat di daerah membuat publik gusar. Rakyat kembali resah, merasa dikhianati oleh kebijakan yang seharusnya melindungi mereka. Harapan agar tambang menjadi jalan sejahtera, justru berubah menjadi ancaman kehilangan hak hidup.
Padahal, rakyat Aceh pernah menaruh harapan besar ketika pemerintahan Mualem berjanji menertibkan tambang ilegal dan memperkuat penambang rakyat. Namun kini, arah kebijakan itu tampak kabur. Investor besar kembali masuk, membawa surat rekomendasi yang mencatut nama pejabat, bahkan disebut-sebut menggunakan nama presiden untuk melancarkan izin.
Sementara itu, ribuan penambang rakyat di Aceh Selatan bekerja dengan alat sederhana, tanpa perlindungan hukum, tanpa akses modal, dan tanpa kepastian. Mereka dianggap “ilegal”, sementara para pemodal besar justru dilindungi oleh sistem yang seharusnya adil.
Ironinya, arah kebijakan nasional sebenarnya sudah berpihak pada rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengutamakan sektor tambang untuk koperasi, BUMD, dan didampingi oleh perguruan tinggi. Kebijakan ini lahir dari semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun implementasinya di Aceh berjalan terbalik. Pemerintah daerah justru sibuk membuka pintu bagi korporasi besar, bukan menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil. Hingga kini, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan banyak kabupaten lain belum memiliki WPR, meski aktivitas tambang rakyat sudah berlangsung puluhan tahun.
Data Kementerian ESDM 2024 memperlihatkan ketimpangan mencolok, dari total 96 izin tambang di Aceh, lebih dari 70 persen dikuasai perusahaan non-lokal. Hanya segelintir yang melibatkan koperasi atau BUMD. Di sisi lain, lebih dari ribuan penambang rakyat masih bekerja tanpa izin resmi. Mereka hidup di tengah dilema antara kebutuhan ekonomi dan ancaman kriminalisasi.
Inilah wajah baru kolonialisme sumber daya, dimana rakyat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Otonomi yang seharusnya membebaskan justru menciptakan ketergantungan baru kepada investor dan elit politik. Kewenangan yang diberikan lewat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mestinya menjadi alat kemandirian, bukan alat barter kekuasaan.
Dari sisi tata kelola, praktik pencatutan nama pejabat untuk memperlancar izin tambang jelas merupakan pelanggaran etika pemerintahan. Ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap semangat good governance. Pemerintah seharusnya menegakkan asas transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, pernah menulis bahwa demokrasi ekonomi hanya bisa hidup jika rakyat diberi ruang untuk mengelola kekayaan alamnya secara mandiri dan berkeadilan. Tanpa itu, ekonomi akan menjadi alat pemerasan oleh segelintir orang. Aceh, yang dulu memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian, kini justru dikuasai oleh oligarki baru dengan wajah lokal.
Dampak ketimpangan ini tidak hanya sosial, tapi juga ekologis. Laporan WALHI Aceh tahun 2023 mencatat, kerusakan hutan akibat aktivitas tambang di wilayah tengah dan barat Aceh mencapai lebih dari 8.000 hektar per tahun. Banjir dan longsor menjadi ancaman rutin. Ironisnya, yang paling menderita adalah masyarakat kecil yakni penambang rakyat, petani, dan nelayan yang kehilangan lahan dan sumber penghidupan.
Rakyat Aceh tidak menolak pembangunan. Mereka hanya menolak ketidakadilan. Mereka tidak menolak investasi, tapi menolak dikuasai oleh modal yang menyingkirkan rakyat. Mereka ingin pemerintah hadir, bukan sekadar memberi izin bagi perusahaan tambang, tetapi memberi perlindungan.
Solusi sebenarnya sederhana, tetapkan WPR, libatkan koperasi, dan kembangkan teknologi pengolahan emas ramah lingkungan yang bisa dijalankan rakyat. Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi contoh pengelolaan tambang berkeadilan, asalkan pemerintah berpihak.
Sudah saatnya Pemerintah Aceh berhenti menjadi perantara kepentingan oligarki. Moratorium izin bagi investor besar harus dilakukan, sambil mempercepat legalisasi tambang rakyat. Pemerintah juga perlu mengaktifkan peran BUMD agar hasil bumi tidak terus mengalir keluar daerah.
Rakyat Aceh sudah terlalu lama menjadi korban janji. Mereka tidak meminta banyak, hanya ingin diakui, dilindungi, dan diberi ruang untuk hidup dari tanah sendiri. Karena sesungguhnya, keadilan yang mereka tuntut bukanlah keadilan dalam wacana, tetapi keadilan yang bisa mereka rasakan setiap kali mereka menambang, bertani, dan menafkahi keluarga.
Sejarah Aceh mengajarkan satu hal bahwa rakyat Aceh bisa sabar, tapi tidak bisa dibohongi terlalu lama. Bila keadilan terus dikhianati, maka luka sosial akan kembali menganga. Dan ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, tidak ada lagi damai yang bisa bertahan.
Kini Aceh berdiri di persimpangan. Apakah kita akan membiarkan tanah ini kembali diterkam oleh harimau kekuasaan ekonomi, atau kita berani menegakkan keadilan bagi rakyat yang sudah terlalu lama menunggu?
Sebab jika tidak, sejarah akan menulis tentang kisah setelah lepas dari mulut buaya konflik, Aceh benar-benar diterkam oleh mulut harimau bernama keserakahan.